“Tadi uang papa limapuluh ribu kan,.. mana kembaliannya..” sebuah kalimat, malam itu menarik perhatian saya. Di sebuah sudut sebuah supermal, saya berdiri sambil menunggu anak saya bermain di sebuah pusat permainan anak di situ. Seperti biasa, memang dalam keramaian seperti itu, sebenarnya saya sedang menikmati kesendirian mengamati segala hal di sekeliling saya. Lalu lalang orang di pusat pertokoan itu, tawa canda anak dan orang tua di situ, kelucuan-kelucuan orang tua yang lebih menikmati suasana tinimbang anak-anaknya yang dibiarkan berjalan bersama pengasuhnya. Atau silang pendapat yang biasa terjadi dalam hubungan keluarga juga sering terlihat di sana, seperti juga yang tertangkap oleh telinga dan mata saya malam itu.
“..lah, kan sudah aku kasih ke papa..” tukas sang anak, dengan nada agak tinggi. Si anak adalah seorang bocah laki-laki kira-kira umur belasan tahun, sementara si ayah, mungkin beberapa tahun lebih tua dari saya.
“..kamu jangan bohong, yaa..” sergah sang ayah, sambil tampak sang ayah menunjuk ke muka sang anak. Sepertinya kesabarannya sudah mulai habis.
“..sudah aku kasih ke papa…!!” teriak si anak sambil pergi menjauh dari ayahnya. Tampak sang ayah kemudian merogoh-rogohkan tangan ke saku, kemudian buka-buka dompet, sampai kemudian tangan kanannya tampak meraih beberapa lembar uang kertas di saku atas bajunya, dahi berkernyit pada raut mukanya, beberapa saat menghitung lembaran uang itu. Tampak seperti ragu, kemudian memasukkan uang itu ke dompet.
Saya tidak tahu persis kejadiannya bagaimana dan akhirnya bagaimana, karena kemudian yang terlihat, sang ayah itu berlalu begitu saja. Hanya saja anehnya, dia berjalan berlawanan arah dengan langkah si anak, tidak berusaha menyusul anaknya. Apa yang ada di kepala saya kemudian hanyalah sebuah asumsi. Asumsi dan dugaan bahwa ternyata si ayah sepertinya telah keliru, sadar akan kekeliruannya, bahwa uang yang mereka ributkan sebenarnya telah diterimanya, hanya dia lupa menaruhnya di saku yang sebelumnya luput dari periksanya.
Saya hanya berharap bahwa bilasaja apa yang terjadi sesuai asumsi saya, maka semoga si ayah segera mencari anaknya untuk meminta maaf telah lupa, bahkan sampai menuduh sang anak berkata bohong.
Suatu saat kita sebagai manusia, pastilah pernah melakukan kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan. Karena memang itulah hakekat manusia. Dan bisa dipastikan, suatu saat kita juga melakukan kesalahan terhadap anak kita sendiri. Tapi sepanjang pengetahuan saya, rupanya kata maaf dari seorang orang tua kepada anaknya adalah sesuatu yang tidak begitu dianggap serius di peri kehidupan kita.
Sesekali cobalah kita merenung, dari sekian kali kita melakukan suatu kesalahan kepada anak kita, kemudian kita menyadari kesalahan itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, berapa kali, kemudian kita datang kepada si anak, menatap matanya, dan dengan kepala tegak berkata maaf kepada sang anak?
Dan kalau hal ini bisa diperluas lagi, kasusnya bisa jadi tidak hanya antara seorang orang tua dengan anaknya, mungkin bisa terjadi seorang karyawan senior kepada karyawan yunior, seorang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Seseorang yang berpangkat lebih tinggi kepada anak buahnya. Adakah kita bisa dengan dada lapang berkata maaf kepada anak, si yunior, yang lebih muda, bawahan, suatu saat bila kita melakukan kesalahan? Mungkinkah kata maaf kepada mereka menurunkan wibawa kita..? Kenapa selalu kita harus menunggu momen lebaran untuk meminta maaf..?
Kata Covey, seorang proaktif adalah orang yang mampu berkehendak bebas. Tentunya bisa dijabarkan –juga- mampu untuk berkehendak bebas terhadap ke-tinggi hati-an orang itu sendiri bila saja diminta untuk proaktif berkata maaf saat melakukan kesalahan terhadap anak, sang bawahan, atau orang yang lebih muda.
Atau.. bila asumsi saya benar atas kejadian sang orangtua-anak di atas, .. anda memilih pergi ke ‘arah yang berbeda’,.. dan berharap itu berlalu sendirinya. Silahkan anda menilai mana yang lebih baik.
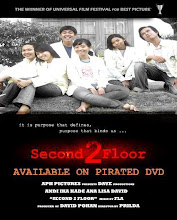




0 komentar:
Posting Komentar